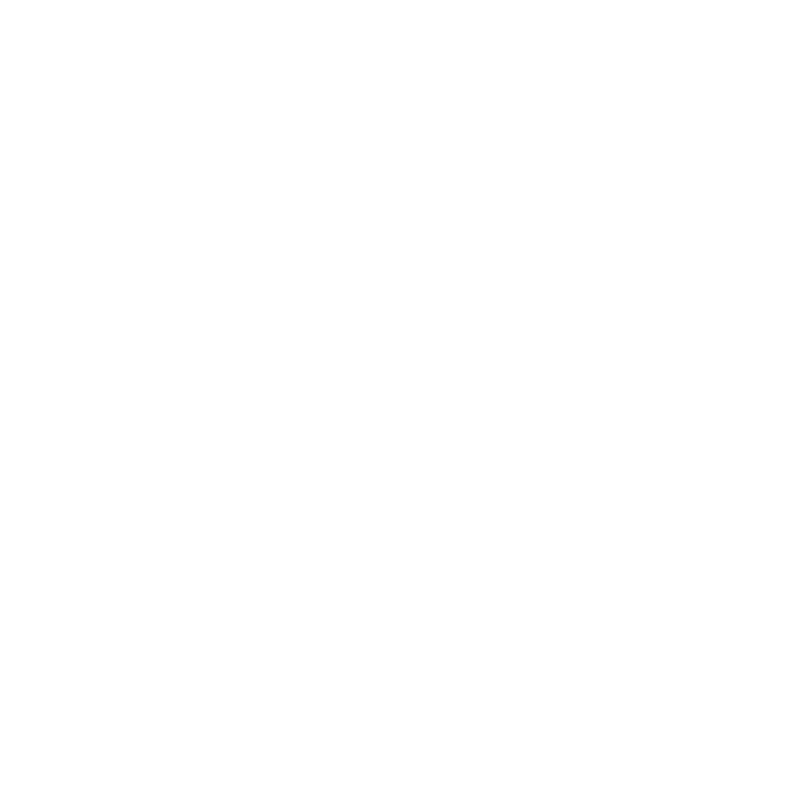Oleh: Agung Laksamana. Penulis adalah Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia dan Dewan Kehormatan Perhumas
Iconomics – Judul “Inikah Akhir Dari Social Network?” sensasional. Judul aslinya adalah “The End of the Social Network”. Judul tersebut menjadi cover story majalah The Economist edisi 3 Februari 2024 lalu. Jadi tentunya masih hangat.
Topik yang diangkat tersebut bukanlah hal baru. Namun tetap menarik disimak. Ada beberapa perspektif disuguhkan.
Perspektif pertama, tahun 2024 adalah tahun politik. Setidaknya ada 64 negara atau sekitar 49% dari total penduduk dunia akan mengadakan pemilu di negara mereka, termasuk Indonesia. Semua akan menggunakan social network sebagai bagian dari strategi kampanye politiknya.
Perspektif kedua, platform sosial media yang sejak awal memiliki fitur sosial dan ajang interaksi dan berbagi konten bersama teman dan keluarga sudah berubah. Social network menjadikan kita sebagai passive users. Artinya kita disuguhkan konten berupa info video dan entertainment. Di sini, social network sudah tidak lagi sosial.
Intinya social network saat ini sudah berkamuflase dalam wujud berbeda. Jaringan sosial online yang hanya menggabungkan interaksi personal dengan komunikasi massa ini telah berubah fungsi. Selain menjadi hiburan, dalam masa kampanye politik platform social network sudah menjadi tempat perdebatan online.
Perspektif ketiga, perubahan fungsi itu telah mengakibatkan terjadinya migrasi. Pengguna mengalihkan percakapan dan argumen mereka dari jaringan terbuka ke private group dan pribadi di platform seperti WhatsApp dan Telegram. Pola komunikasi yang telah menjadi tersegmentasi itu bagi para politisi dan pengikutnya tentunya memberikan dampak besar bagi aktivitas kampanye politik yang dilakukan.
Gardiner, perusahaan riset pasar, mengungkap temuan sekitar 61% orang di Amerika mengatakan mereka menjadi lebih selektif tentang hal yang mereka posting di media sosial. Ketika ditanya, bagaimana mereka memberi rekomendasi film, misalnya survei Morning Consultant menunjukkan ada 43% memilih dengan teks atau email dan hanya 30% akan posting di media sosial.
Bahkan, menurut Head of Instagram, Adam Mossert, tahun lalu saja lebih banyak foto dan video yang dibagikan melalui pesan langsung (direct messaging) daripada yang diunggah feed. Semua sharing mengarah ke arah tersebut. Intinya, bentuk komunikasinya sudah tidak massif namun personalized.
Meta, perusahaan induk Facebook, telah berusia 20 tahun dengan 3 miliar pengguna aktif telah membuktikan pengaruhnya. Kekuatan Facebook sebagai social network harus diakui. Social media yang dirancang Mark Zuckerberg ini bisa membangun gerakan sosial yang sukses seperti #MeToo, #BlackLivesMatter hingga Arab Spring hingga kerusuhan di Gedung Capitol Washington DC beberapa waktu lalu.
Kini, fakta menunjukkan bahwa tren social network yang dibangun oleh Facebook itu secara perlahan mulai menghilang. Alasan utamanya adalah TikTok. TikTok yang muncul sejak 2017 dengan video-video pendeknya begitu cepat menarik perhatian generasi muda. Data The Economist menunjukkan rata-rata orang Amerika menghabiskan waktu 40 menit untuk menonton berbagai video di media sosial mereka. Angka itu naik dari 28 menit pada tiga tahun sebelumnya.
Meta sebagai induk perusahaan Facebook, Instagram dan WhatApp, segera bereaksi. Meta menambahkan fitur video. Misalnya reels untuk Facebook dan Instagram. Hal yang sama dilakukan oleh Pinterest dengan Watch, Snapchat dengan Spotlight, dan YouTube dengan Shorts.
Lalu, jika mundur 10 tahun ke belakang, Mark Zuckerberg pernah mengatakan bahwa Facebook di suatu hari kelak bakal menjadi newsfeed, koran yang dipersonalisasi dengan sempurna bagi semua orang di dunia. Tapi kenyataan itu tidak terjadi. Data Facebook menunjukkan bahwa berita hanya menyumbang kurang dari 3% dari yang pengguna lihat di Facebook.
Tahun 2023, jumlah lalu lintas internet yang dikirim dari Facebook ke perusahaan media turun drastis hingga 48%. Ujungnya, Buzzfeed News tutup dan Vice News juga secara drastis cut back. Alhasil, orang-orang melihat berita lebih sedikit dalam feed mereka. Otomatis mereka jarang berbagi atau mengomentari berita secara publik. Tahun lalu saja hanya 19% orang yang sharing berita dari feed-nya yang sebelumnya 28% di tahun 2018. Dengan kata lain, kita semua menjadi passive news consumer artinya membaca berita namun tidak berkomentar, tidak sharing dan pada akhirnya tidak ada engagement sama sekali.
Dalam masa-masa pemilu seperti sekarang, apa yang dicari oleh publik, termasuk di Indonesia? Satu hal yang sudah pasti, tren saat ini bahwa publik sudah tidak mau berdebat di ranah terbuka media sosial seperti beberapa tahun lalu. Pengguna sekarang lebih mencari platform yang dapat membuat kita semua sebagai calon pemilih, lebih menyukai tontonan konten lucu yang bisa membuat tertawa atau momen serupa lainnya. Di sini tentunya diperlukan kreativitas.
emua itu terjadi karena para pemilih sudah tidak mencari konten yang mengarah pada perdebatan atau bahasan politik. Kalaupun mau, pemilih beralih ke platform seperti obrolan grup pribadi, bukan platform terbuka. Mengapa? Karena mereka tidak ingin dikucilkan oleh teman-teman atau keluarga mereka sendiri dan berpikir, “Aduh, sudah mulai lagi nih dia bahas topik itu!”
Di Indonesia, menurut The Economist , TikTok dengan pengguna terbesar setelah Amerika Serikat, terbukti sangat strategis sebagai saluran bagi politisi bersaing untuk mendapatkan suara terutama dari kalangan kaum muda. Di Indonesia, TikTok telah berhasil meningkatkan popularitas personal capres dan caleg jauh lebih efektif daripada membahas substansi kebijakan.
Dengan adanya perubahan tren tersebut, bisa digarisbawahi ternyata pengguna termasuk Anda dan Saya sudah tidak lagi membaca postingan. Tendensi perilaku kita semua saat ini adalah watching (menonton) video-video. Not posting but watching!
Inikah pertanda akhir dari Social Network?
Sumber:
https://www.theiconomics.com/icon-opinion/inikah-akhir-dari-social-network/#google_vignette