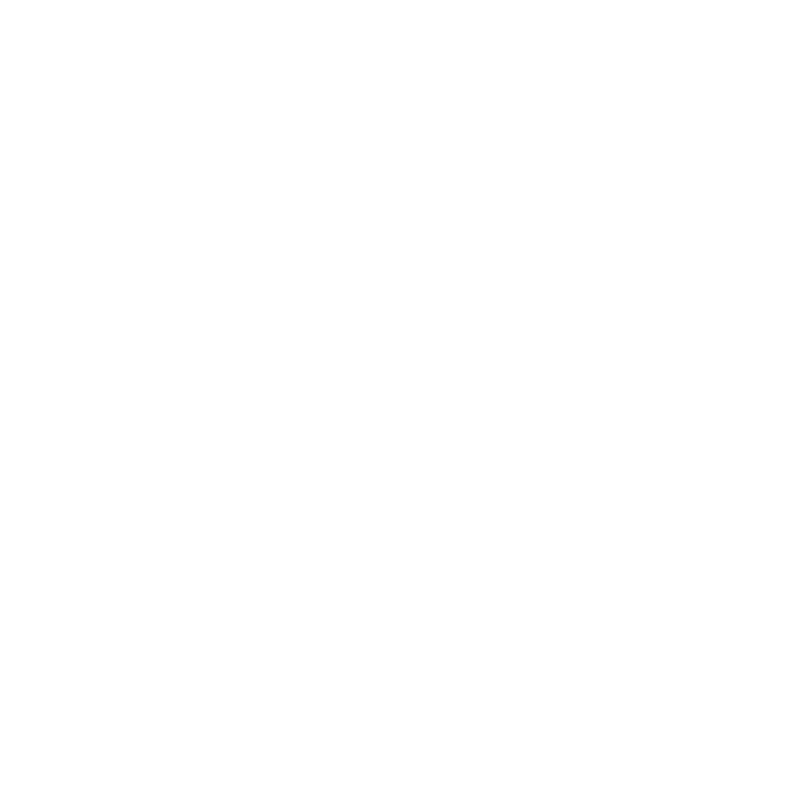![]()
Pada 2018, sekitar lima tahun sebelum ChatGPT lahir, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berbicara di Konferensi VivaTech di Paris. Dia percaya bahwa Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki layanan publik, walau dalam pengembangan dan penggunaannya harus terus memperhatikan etika dan sosial.
Hari ini, pada 2023, sadar atau tidak, keberadaan AI makin nyata di sekeliling kita. Kemunculan AI bukan hanya soal revolusi teknologi, tetapi bisa jadi menjadi revolusi budaya. AI akan mengubah cara pandang kita melihat dunia kerja dan masyarakat. Ini semua sudah hampir menjadi realita!
Baiklah, di sekeliling kita misalnya, perusahaan Suryadhamma Investama mengangkat Direktur AI pertama di Indonesia yang bernama Ardi, TVOne telah memiliki tiga presenter AI, dan sekolah dasar di Cina menggunakan AI untuk membantu guru-guru mereka. Bahkan Dragon Websoft, sebuah perusahaan game yang berkantor pusat di Fuzhou, Cina menunjuk robot humanoid virtual bertenaga AI bernama Tang Yu sebagai CEO dari anak perusahaannya, Fujian NetDragon Websoft.
Namun, pernyataan akhir Presiden Macron dalam opini saya yang jauh lebih kritikal, yaitu ketika menavigasi era baru ini, kita harus memastikan AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang etika dan nilai sosial.
Teknologi AI memang dahsyat. “Dia” bisa membuat analisa trend, powerpoint, storyboard, desain, serta menghasilkan konten visual dan grafis seperti infografis, animasi, grafik, dan lainnya. Terlepas dari semua itu, AI telah menjadi salah satu teknologi paling penting yang akan memengaruhi—-dan mentransformasi berbagai industri global saat ini. Dan, tidak terkecuali dunia public affairs, public relations, dan komunikasi.
Public affairs yang memiliki peran fungsi strategis, melibatkan pengelolaan hubungan antar-organisasi, masyarakat, dan pemerintah akan terdampak dengan keberadaan AI. Sejak lama, sektor ini mengandalkan metode komunikasi tradisional, seperti lobi, dialog, konferensi, focus group discussion (FGD), campaign, siaran pers hingga press conference. Hadirnya AI akan membuat lanskap public affairs berubah dengan cepat.
Sebagai contoh, salah satu peran public affairs adalah memahami sentimen publik perihal isu-isu yang tengah berkembang dan kritikal bagi sebuah organisasi. Melalui AI, semua bisa dipantau secara real time sehingga praktisi public affairs bisa membentuk atau memberikan input seputar opini publik, memprediksi tren,menyederhanakan komunikasi hingga tailor-made content agar relevan kepada para pemangku kepentingannya (stakeholders).
Dengan adanya bantuan AI, organisasi dan perusahaan bisa menentukan action apa yang harus dilakukan, yang bisa diterima oleh publik secara positif sehingga end-goal dengan para stakeholders bisa tercapai. Otomatisasi, akselerasi, verifikasi, dan empati. Inilah empat kata yang menggambarkan—-sekaligus menjadi catatan—-fungsi AI dalam dunia public affairs, menurut hemat saya.
AI bisa mempermudah aktivitas rutin dan terkesan monoton dengan otomatisasi. Tugas-tugas praktisi seperti menjawab pertanyaan, menjadwalkan pertemuan, mencari kata apa yang paling banyak dicari dalam search engine optimization (SEO), menerjemahkan audio ke teks bisa dilakukan dengan bantuan AI. Dengan demikian, tugas, peran, dan fungsi praktisi public affairs bisa fokus pada kegiatan yang lebih strategis, seperti mengembangkan dan menerapkan strategi advokasi dan komunikasi—-bukannya taktikal.
Salah satu keuntungan terbesar dari penggunaan AI dalam urusan public affairs adalah kecepatan menganalisa jumlah data yang besar secara cepat. Algoritma AI dapat memproses dan menganalisa data dengan cepat, mengidentifikasi pola dan tren yang sulit, atau bahkan tidak terdeteksi secara manual—-padahal merupakan informasi yang berharga sehingga akselerasi pun tercipta.
Forbes melansir, AI akan berdampak signifikan terhadap perekonomian pada 2035 dengan menaikkan produktivitas hingga 40 persen atau lebih. Laporan itu juga memprediksi, AI akan mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 1,7 persen terhadap 16 industri pada 2035. Artinya, dalam organisasi, AI dapat membantu menyederhanakan dan mengakselerasi banyak hal. Intinya efisiensi dan penghematan biaya, dua faktor utama yang pastinya diminta manajemen agar bisa meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan biaya perusahaan.
Ketiga, verifikasi. AI memang adalah kecerdasan buatan yang bisa mempermudah tugas praktisi public affairs. Namun, sangat terbuka dan besar kemungkinan bahwa AI melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data, menganalisanya sehingga membuat praktisi salah membuat keputusan. Itulah mengapa kita jangan terlena dengan segala bantuan dari AI.
ChatGPT misalnya, salah satu generative AI buatan Sam Altman banyak dimanfaatkan para siswa untuk berlaku curang. Sejumlah sekolah di New York, Amerika dan universitas di Australia kini telah melarang penggunaannya.
Tidak bisa dimungkiri, tantangan signifikan adalah potensi adanya bias pada algoritma AI. Jika data algoritma yang digunakan salah, maka output-nya bisa keliru, dan berakibat konsekuensi serius. Kita tetap harus melakukan verifikasi dan konfirmasi. Sebab, kita tidak bisa “memarahi, memecat, atau meminta AI untuk bertanggung jawab” terhadap kesalahan yang tercipta. Intinya, praktisi haruslah tetap gunakan prinsip, Trust but verify!
Opini Satya Nadella, CEO Microsoft, tentang AI, saya rasa sangatlah relevan bahwa we need to keep humanity in the forefront of developments in AI and ensure that AI remains our tool, not our master.
Pada akhirnya, kolaborasi dengan AI akan membantu praktisi public affairs untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, melalui otomatisasi, akselerasi dan kreativitas. Namun, praktisi Public Affairs tetap tidak boleh meninggalkan pentingnya verifikasi.
Sepintar-pintarnya AI, dia hanyalah alat bantu bukan penguasa kita. Plus, satu hal penting lagi yang tidak dimiliki AI: empati!
Penulis: Agung Laksamana, Ketua Public Affairs Forum Indonesia & Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia
Artikel ini dimuat juga di Warta Ekonomi berikut:
https://wartaekonomi.co.id/read496111/ai-vs-public-affairs-kolaborasi-x-verifikasi